Berita / Pojok /
Mari Kita Main Salah Menyalahkan

Oleh: Prof. Sudarsono Soedomo*)
Mencari kesalahan pihak lain dalam suatu peristiwa adalah pekerjaan paling mudah di dunia. Ia tidak memerlukan data lengkap, tidak butuh kesabaran, apalagi keberanian intelektual. Cukup emosi, sedikit kecurigaan, dan satu dua dugaan—maka kesalahan pun segera menemukan alamatnya. Ironisnya, kesimpulan yang lahir dari proses saling menyalahkan hampir selalu terasa memuaskan, sekaligus hampir pasti keliru. Namun siapa peduli; di sini kita sedang bermain di dunia yang salah.
Tulisan ini pun bagian dari permainan itu. Ia tidak menawarkan kebenaran, tidak menjanjikan ketepatan analisis, bahkan tidak berpura-pura netral. Kita sedang bermain di dunia yang salah, dan di dunia ini, salah dan benar boleh saling bertukar posisi tanpa merasa bersalah.
Dalam setiap banjir besar, pola menyalahkan selalu berulang. Kementerian yang mengurusi hutan dan sumber daya alam menjadi sasaran empuk. Terlalu mudah, bahkan terlalu rutin. Mungkin salah, mungkin juga tidak. Tapi karena sudah sering, menyalahkan mereka terasa kurang menggugah. Maka mari kita mencari pihak lain. Bagaimana kalau kita menyalahkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan?
Apa hubungannya dengan banjir? Ada. Atau setidaknya dapat diada-adakan. Ingat, kita sedang bermain di dunia yang salah. Di sini, mengada-ada tidak dilarang, asal terdengar masuk akal.
Fakta yang sering disebut—dan sering pula sekadar dihafal—adalah adanya puluhan juta hektar areal tidak berhutan di dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Angkanya bervariasi, tetapi 30 juta hektar kerap disebut. Di saat yang sama, kemampuan anggaran negara untuk menghutankan kembali hanya sekitar 30 ribu hektar per tahun. Dengan asumsi keberhasilan 100 persen—yang jelas juga bagian dari dunia yang salah—dibutuhkan seribu tahun untuk memulihkan semuanya. Ringkasnya, mengandalkan anggaran negara untuk penghutanan kembali bukanlah solusi, kecuali kita rela menunggu satu milenium.
Pilihan yang sedikit lebih waras adalah melibatkan rakyat. Ini bukan gagasan baru dan bahkan sudah terjadi, terutama di Pulau Jawa. Di sana, hutan rakyat tumbuh bukan karena perintah negara, melainkan karena ia masuk akal secara ekonomi. Kayu dihargai dengan baik. Bahkan, jika dihitung secara sederhana, penerimaan rata-rata per hektar per tahun dari hutan rakyat dapat menyamai—atau mendekati—penerimaan kebun sawit.
Tentu ini tidak berarti bahwa Pulau Jawa kebal terhadap banjir atau cuaca ekstrem. Tidak ada klaim seajaib itu. Yang ingin dikatakan lebih sederhana: rakyat bersedia menanam pohon jika insentifnya masuk akal. Hutan tumbuh bukan karena pidato, melainkan karena harga.
Pertanyaannya kemudian: mengapa pola ini tidak terjadi di luar Pulau Jawa, padahal ketersediaan lahan jauh lebih luas? Di sinilah permainan salah menyalahkan menjadi menarik. Industri pengolahan kayu di luar Jawa sangat sedikit. Logistik mahal, pasar jauh, dan mata rantai nilai putus di tengah jalan. Maka mari kita arahkan jari ke Kementerian Perindustrian. Bukankah tugas mereka mengembangkan industri? Mengapa industri pengolahan kayu tidak tumbuh merata di luar Jawa?
Lalu giliran Kementerian Perdagangan. Kebijakan pelarangan ekspor kayu glondongan dan setengah jadi memang dimaksudkan untuk mendorong industri hilir di dalam negeri. Maksudnya mulia. Namun di dunia yang salah, niat baik sering menghasilkan akibat yang canggung. Ketika industri pengolahan tidak tumbuh, larangan ekspor justru menekan harga kayu di tingkat rakyat. Harga yang tidak menarik membuat rakyat malas menanam. Rakyat yang tidak menanam membuat lahan tetap terbuka. Lahan terbuka memperbesar limpasan air. Dan limpasan air, ketika hujan ekstrem datang, menjelma banjir.
Apakah ini rangkaian sebab-akibat yang solid secara ilmiah? Belum tentu. Apakah ini menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks? Jelas iya. Tapi sekali lagi, kita sedang bermain di dunia yang salah. Di dunia ini, rantai logika yang rapuh tetap boleh dipakai, selama terdengar rasional dan mengisi ruang debat publik.
Barangkali justru di situlah nilai tulisan ini. Ia bukan untuk menyudutkan kementerian tertentu, melainkan untuk menyingkap kebiasaan kita sendiri: kecenderungan mencari kambing hitam sektoral atas persoalan yang bersifat struktural. Banjir tidak pernah lahir dari satu kementerian, satu regulasi, atau satu komoditas. Ia lahir dari sistem kebijakan yang terfragmentasi, insentif yang timpang, dan keberanian yang kurang untuk mengakui bahwa banyak keputusan “rasional” berdampak irasional ketika dijumlahkan.
Di dunia yang benar, kita mungkin akan bertanya: bagaimana menyelaraskan kebijakan industri, perdagangan, kehutanan, dan lingkungan agar saling memperkuat? Namun di dunia yang salah, kita cukup menunjuk, menuduh, dan merasa lega karena telah menemukan tersangka.
Akhirnya, barangkali itulah banjir yang sesungguhnya: banjir kesimpulan instan, banjir kepastian palsu, dan banjir kenyamanan moral—yang datang jauh lebih cepat daripada meluapnya air sungai.
*) Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB





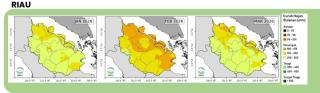


Komentar Via Facebook :