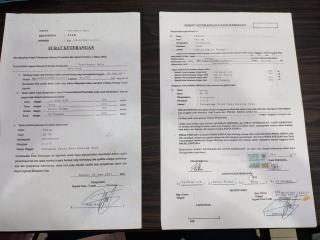Terpopuler
-
Angka Ajaib 25 Juta: Catatan atas PP 45 Tahun 2025
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Ribuan Masyarakat Riau Minta Perlindungan Menhan
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Ribuan Hektar Kelapa Sawit Ditindak Satgas PKH, Petani Tebo Merapat ke Aspek-Pir
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Menyoal TNTN
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Bikin Jantungan Penertiban Kawasan Hutan
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Beredar SK Kades di Siak Jual Lahan PT SSL
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
DMO Sawit untuk B50, CPO dan TBS Diprediksi Jatuh Bebas
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Berubah Jadi Kebun Sawit, Satgas PKH Didesak Tertibkan Tahura SSH
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Benarkah Pohon Sawit Tak Bisa Menyerap Air? Ini Penjelasan Ahli
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
1.200 Hektar Kebun Sawit di Asahan Siap Dialihkan Jadi Sawah Tadah Hujan
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
BPDP hingga Perusahaan Sawit Takjub Melihat Mahasiswa INSTIPER Praktik Lapangan
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Klaim Kawasan Hutan Buat PSR di Kalteng Terseok-Seok
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Jurus Fokus 2+1 Astra Agro: Upaya Menjawab Tantangan Zaman Industri Sawit
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Ram Sawit Ilegal di Kawasan Hutan di Kuansing Ditutup
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam. -
Ribuan Hektare Kebun Sawit PBS di Kalteng Disegel Satgas PKH
Jakarta, elaeis.co – Pernyataan tegas Indian Food and Beverage Association (IFBA) yang melawan kampanye negatif minyak sawit mendadak jadi tamparan keras. Bukan cuma buat kelompok anti sawit global, tapi justru menghantam balik negara produsen utama seperti Indonesia. Ironis, saat negara pengimpor besar membela sawit dengan data dan sains, di dalam negeri sendiri komoditas ini malah terus digerus narasi buruk. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sikap IFBA sebagai sinyal keras bahwa ada yang keliru dalam cara Indonesia memperlakukan sawitnya sendiri. “Untuk pertama kali negara pengguna minyak nabati sawit terdepan melawan kampanye negatif sawit. Ini justru menjadi pukulan berat bagi negara produsen minyak nabati sawit seperti Indonesia,” kata Dr. Gulat. Menurutnya, India melalui IFBA membela sawit bukan asal bunyi. Mereka berdiri di atas kepentingan ketahanan pangan, harga terjangkau, dan pendekatan ilmiah. Sebaliknya, di Indonesia, sawit seolah terus dijadikan kambing hitam segala persoalan lingkungan dan sosial. “Di saat negara importir seperti India membela sawit secara terbuka dan rasional, Indonesia justru dibanjiri narasi bahwa sawit itu tidak baik. Isu ini seperti tak pernah berhenti diproduksi,” ujarnya. Narasi negatif itu, lanjut Gulat, menyebar seperti asap tebal, pelan tapi mencekik. Media online, media cetak, hingga ruang-ruang diskusi publik dipenuhi cerita suram soal sawit. Dampaknya, persepsi publik pun ikut terdistorsi. “Memang tidak semua masyarakat terpengaruh. Tapi kebanyakan sudah terbuai dan percaya dengan kampanye negatif sawit yang dibangun secara masif, terencana, dan terstruktur lewat berbagai media,” tegasnya. Kondisi ini, kata dia, bukan cuma soal citra. Ini sudah menguras energi bangsa. Terlalu banyak kementerian dan lembaga terlibat dalam urusan sawit, namun tanpa satu komando yang jelas. Alih-alih solid, yang muncul justru kebijakan tumpang tindih dan regulasi yang saling menikam. “Terus terang, energi kita habis sendiri. Banyak kementerian dan lembaga ambil peran di sawit, tapi tidak terintegrasi. Pada akhirnya, ‘lawan sawit’ itu justru bersifat domestik, dari dalam negeri sendiri, termasuk lewat regulasi,” ujar Gulat dengan nada getir. Ia menilai situasi ini berbahaya. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tapi tulang punggung ekonomi jutaan petani. Jika kampanye negatif dibiarkan makin brutal, efek domino ke petani kecil tak terelakkan, dari harga TBS tertekan, akses pasar menyempit, hingga stigma sosial di tingkat tapak. Untuk itu, APKASINDO mendorong pembentukan lembaga khusus yang mengurusi sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya soal produksi dan ekspor, tapi juga perang narasi. “Sudah saatnya dibentuk badan khusus yang mengurusi sawit secara terintegrasi, termasuk kampanye positif sawit. Kami berharap Presiden Prabowo bisa segera mengantisipasi masifnya kampanye negatif sawit di dalam negeri dengan mendirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI),” ujarnya. Dr. Gulat juga mengingatkan posisi strategis India bagi Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, India konsisten menjadi salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Fakta ini, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia bercermin. “India itu pasar besar kita. Mereka membela sawit dengan lantang karena tahu manfaatnya bagi rakyatnya. Kita seharusnya malu. Di sana sawit dibela, di sini justru sering disudutkan,” katanya. Pernyataan keras APKASINDO ini muncul menyusul sikap resmi IFBA yang menilai label No Palm Oil atau Palm Oil Free lebih sebagai strategi politik pemasaran ketimbang informasi gizi berbasis sains. IFBA menegaskan, label tersebut menyesatkan konsumen dan tidak sejalan dengan pedoman resmi maupun fakta ilmiah. Bagi APKASINDO, sikap IFBA seolah membuka mata dunia. Bahwa kampanye anti sawit tak selalu soal lingkungan atau kesehatan, tapi kerap sarat kepentingan. Dan di Indonesia, kampanye itu dinilai sudah melampaui batas, kian brutal, kian bising, dan perlahan menggerogoti kepentingan petani sendiri. Saat dunia mulai bicara dengan data, Indonesia justru sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri. Sawit pun berdiri di persimpangan, antara dibela atau terus dihantam dari dalam.